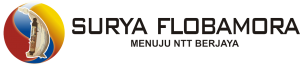DATUKELI, SURYAFLOBAMORA.COM- Belum juga usai linangan air mata kami karena kehilangan Pater Nadus Kota, SVD, seorang imam SVD yang mengabdikan diri sekian lama di dunia pendidikan, datang kabar duka kepergian Pater Lipus Panda, SVD.
Lipus Panda, nama ini sudah lama tak asing untuk saya sejak di Seminari San Dominggo Hokeng, Larantuka. Romo Gius Lolan, Pr, teman seangkatan dengan Lipus, selalu menceritakan siapa itu Lipus Panda, selain tentang Pater Paul Budi Kleden. Lipus, cerita Gius, adalah seorang yang selalu menunjukkan kecerdasannya dalam diam, dalam kerendahan hati seorang kampung tidak hanya ketika mengenyam pendidikan di Seminari San Dominggo Hokeng, tetapi juga ketika menjadi mahasiswa di STFK Ledalero. Dan saya secara pribadi menyimpan kisah kecil itu hingga ketika bertemu langsung dengan Lipus di Ledalero.
Usai bekerja beberapa tahun di tanah misi Ghana dan kembali menjadi formator di seminari Ledalero, Lipus mengambil magister dalam bidang sosiologi di London School of Economics and Political Sciences, sekolah yang terkenal amat seram dalam ilmu ilmu sosial. Awal tahun 2002, Lipus kembali ke Ledalero dan mengabdikan diri sebagai dosen sosiologi. Saya dan teman teman seangkatan adalah angkatan kedua yang diajar Lipus untuk mata kuliah SOSIOLOGI AGAMA, suatu mata kuliah yang menurut saya adalah sajian yang dikemas dengan sangat indah, dalam dan sistematis oleh Lipus. Mendengar kuliah Lipus, seolah kesadaran kami digedor untuk terus memahami bahwa perkara perkara sosial yang tampak sepeleh di mata kebanyakan orang bisa dibedah dan diangkat untuk memahami perkara perkara hidup yang amat serius di dalam masyarakat. Ya…serupa perkara secangkir kopi a la Sosiolog Charles Wright bisa dibedah untuk memahami geliat kapitalisme di dalam masyarakat. Atau serupa perkara prosesi di Larantuka bisa dibedah untuk melihat apakah keramaian dalam prosesi menunjukkan secara serius kesungguhan hidup keagamaan para peziarah, atau gambaran dari keluh kesah makhluk yang nasibnya sedang tertindas.
Tentang ini, Lipus, saya boleh katakan, adalah dosen yang sangat luar biasa di mata para mahasiswanya. Dia adalah satu dari sedikit dosen saya yang memberikan kuliah dengan sangat sistematis, meski penampilannya tetap seperti seorang papalele dari pegunungan Detukeli: sederhana, apa adanya. Kalau melihat penampilannya, saya semula tak terlalu diyakinkan bahwa dia seorang dosen yang luar biasa. Tapi yang tampak di mata saya itu berubah ketika Lipus sudah bicara di depan kelas. Ya, banyak memang dosen yang cuma menang dalam penampilan, tetapi amat minim dalam disiplin ilmunya, mudah tersinggung, dan baperan, apalagi ketika dikritik oleh mahasiswanya.
Lipus bukan figur dosen yang baperan. Kuliahnya sistematis, dan tanggapannya atas aneka pertanyaan kritis dari mahasiswa tetap menunjukkan dirinya seorang yang sangat berwibawa dalam disiplin ilmunya. Tapi ini tidak hanya tampak ketika ia memberikah kuliah. Tampak juga misalnya dalam sedikit artikel ilmiah yang ditulisnya. Dalam Jurnal Ledalero, edisi pertama, artikelnya berjudul Mempertimbangkan Pemberdayaan Mencari Kiat Analitis Buat Para Agen Agama, Lipus benar benar menunjukkan dirinya seorang intelektual yang sangat dekat dengan perkara hidup sosial. Artikel ini malah dijempoli sosiolog Ignas Kleden sebagai artikel terbaik dari semua artikel dalam jurnal perdana.
Tapi tidak hanya dalam kuliah, tidak hanya pula dalam tulisan. Dia pun tetap menunjukkan dirinya seorang intelektual meski dalam urusan urusan pinggiran, seperti menghimpun para pendorong gerobak di kota Maumere, hal yang jarang bisa disentuh oleh seorang yang terbiasa dengan urusan belakang meja. Sudah bukan rahasia bahwa banyak yang menamai dirinya orang belakang meja enggan atau amat sungkan untuk terjun ke bawah, apalagi untuk hadir bersama misalnya dengan para pendorong gerobak. Tapi Lipus tidak demikian. Lipus barangkali tahu benar bahwa seorang hanya bisa jadi besar, termasuk jadi besar dalam disiplin ilmu kalau seperti Yesus, berani turun dan basuh kaki para murid.
Dalam urusan turun ke bawah ini, Lipus tetaplah seorang intelektual. Apakah kewibawaannya luntur gara gara ini? Tidak sama sekali! Dalam suatu kesempatan kapitel provinsi SVD Ende di Ledalero, saya (masih sebagai frater) bersama Lipus sebagai tim secretariat harus menyiapkan review dan melaporkannya setiap pagi kepada kapitularis saat hendak membuka kapitel. Lipus mengajarkan saya untuk membuat review yang singkat, tetapi berisi. Isi, kata Lipus, bukan dilihat dari rumusan yang bertele-tele, tapi dari hal, seperti kata para filsuf bahasa, sepotong kata membawa sepotong dunia. Dengan lain perkataan, bukan penampilan, tetapi kedalamanlah yang dibutuhkan. Bukan soal dengan para pendorong gerobak, tetapi harga dari keterlibatan sosiallah yang harus dilihat. Bukan soal di Detukeli, tetapi memaknai hidup secara benar di Detukeli. Itulah harga yang harus terus diperjuangkan seorang intelektual,
Dan Lipus sudah memberi makna, harga atas pengabdiaannya yang terasa masih terlalu singkat. Dia sebenarnya masih sangat dibutuhkan, tetapi sakit dan akhirnya kematian membuat kita, semua yang mencintainya dengan berat hati mengatakan mau bagaimana lagi. Dia pergi, tetapi menggores kenangan yang jarang dimiliki kebanyakan dosen, para intelektual. Dia mungkin tak sehebat Anthony Giddens gurunya di London School of Economics and Political Sciences. Dia mungkin tak sehebat sosiolog Charles Wright, sosiolog kesayangannya. Tetapi dari perkara serupa secangkir kopi di pagi hari dia sudah mengingatkan bahwa hidup sesingkat dan sesederhana apapun perlu dimaknai secara benar.
Selamat jalan Lipus!
Dari muridmu yang sedang mengendus makna di Detukeli
Penulis: Charles Beraf